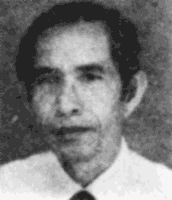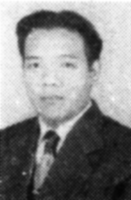Sejarah Kalender
Kalender
atau tanggalan, adalah suatu cara yang teratur dan disepakati untuk
menandai unsur rentang waktu yang tidak terbatas dalam daur dan hukum
tertentu. Kegunaannya sudah tentu tergantung dari komunitas yang
menyepakatinya. Misalnya untuk menentukan daur musim, kegiatan religius,
mengukur panjang kurun dan sebagainya. Daur dan aturannya tentu saja
tidak lepas dari ikatan budaya komunitas tersebut. Ada kalender yang
daurnya didasarkan pada letak benda langit (misalnya kalender surya,
kalender candra), dan ada pula yang tidak sama sekali (misalnya kalender pawukon kita).
|
|
Kalender yang berdasarkan letak
benda langit juga memiliki aturannya sendiri-sendiri dalam penerapannya.
Beberapa kalender mencermati setiap perubahan dengan observasi dari
waktu ke waktu, misalnya penentuan garis busur cahaya pertama dipermukaan bulan, pada kalender ritual Islam.
Kalender seperti ini tidak mungkin dirinci sebelumnya. Karena hasil
observasinya bisa bergantung kepada cuaca dan peralatan yang digunakan.
Sering terjadi ricuh atau standar ganda dalam kesepakatannya. Untuk
keperluan duga dini (forecast) dan percetakan, tetap diperlukan kalender
perkiraan, sedang ketelitiannya nanti akan sama-sama dimaklumi perihal
geser menggesernya.
Kalender Gregorian (Masehi) juga berdasar benda langit - matahari. Observasi tidak mutlak diperlukan dari waktu ke waktu. Karena itu pendahulunya, kalender Julian,
menerapkan kekeliruan berlarut-larut sampai 15 abad lebih lamanya.
Karena itu kalender Julian direnovasi menjadi Gregorian dengan
memperbaiki aturannya, dan memusnahkan 10 tanggal agar cocok dengan
patokan semula.
|
|
Kalender dapat dipakai mengingatkan orang
kepada sesuatu. Apakah yang akan terjadi, yang sedang berlangsung, dan
yang telah lalu. Sebagai bentuk ketidak berdayaan orang melawan
perputaran waktu diwujudkan dalam perhitungan-perhitungan. Sehingga
orang sadar, kapan akan datang masa yang panas terik maupun masa yang
bersimbah air. Akhirnya semakin teliti ke pengaturan untuk bertani,
berburu, mengungsi, mencari ikan dan hampir segala segi kehidupan.
Semuanya tercurah dalam kalender. Kalender adalah suatu bentuk
pengaturan komunikasi kita dengan alam semesta.
|
|
Menurut perkiraan (Fraser, 1987)
ada sekitar 40 macam kalender masih dipakai sampai saat ini. Terdiri
dari kalender astronomis dan non astronomis. Pada keduanya, umumnya
salah satu patokannya adalah hari (rotasi : putaran bumi pada porosnya), bulan (revolusi: putaran bulan mengelilingi bumi), dan tahun
(revolusi: putaran bumi mengelilingi matahari). Kerancuan muncul karena
patokan-patokan tersebut tidak mutlak konstan. Ada pergeseran sepanjang
waktu. Sekalipun secara matematika dapat dituliskan rumus hingga 15.000
angka panjangnya, tetap tidak terdefinisikan. Mari kita lihat
persoalannya.
|
|
Satu tahun tropis didefinisikan
sebagai jangka waktu rata-rata yang diperlukan oleh matahari untuk
pergi dan kembali lagi ke titik balik tepat di garis katulistiwa. Jangka
waktunya didekati dengan rumus orbit Laskar (1986) adalah
JD adalah bilangan hari Julian.
Penyimpangan antara kenyataan dengan angka rata-rata ini hanya
beberapa menit saja tiap tahunnya. Perhatikan bahwa dalam T, selisih
dengan bilangan Julian dibagi dengan konstanta 36525 yang merupakan
angka jadian dari 365.242189... di atas. Bilangan Julian dan rumus ini
pula yang dipergunakan dalam semua perhitungan kalender dan pawukon di babadbali.com.
|
|
Satu bulan Synodic didefinisikan
sebagai jangka waktu rata-rata antara titik temu posisi bulan dan
matahari didasarkan pada phase bulan (penanggal / panglong). Panjangnya
diukur menggunakan pendekatan teori Chapront-Touze dan Chapront (1988):
Sekali lagi JD adalah bilangan hari Julian.
Penyimpangan antara kenyataan dengan angka rata-rata (deviasi) ini
adalah sampai 7 jam. Dengan demikian kira-kira 1 tahun candra adalah 354.36707 hari
|
|
Dari rumus-rumus di atas, nampak
bahwa daurnya berubah perlahan seiring waktu. Teori pendekatan di
ataspun masih terus diperbaiki hingga setepat-tepatnya.
Ada 3 macam kalender yang dihasilkan dari
perhitungan di atas: Kalender surya (solar calendar), kalender candra
(lunar calendar), dan kalendar suryacandra (luni-solar calendar). Dalam
kalender suryacandra, kadang-kadang satu bulan candra utuh disisipkan
untuk mengejar panjang tahun surya. Contoh dari kalender ini adalah
kalender Cina, dan kalender Yahudi. Kalender Saka Bali mungkin mendekati suryacandra, hanya ketentuan untuk itu masih sedang banyak dipergunjingkan.
|
|
Kalender non-astronomik di antaranya adalah kalender pawukon dan wewaran
di Bali. Kalender ini tidak memperdulikan posisi astronomik
sama-sekali. Namun pada penggunaannya, tidak dapat dipisahkan dari
penggunaan kalender Saka Bali yang sifatnya sangat khusus dalam khasanah
perhitungan kalender di dunia.
|
|
Banyak upakara dan upacara yadnya, serta piodalan pura
yang berdasarkan pawukon dalam menentukannya, namun banyak juga yang
menggunakan penanggal dan panglong dalam kalender Saka. Demikian pula
perhitungan ala-ayuning dewasa (baik buruknya hari).
Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bali tetap juga menggunakan kalender Gregorian yang ditetapkan secara internasional. Adanya tiga kalender yang digunakan setiap waktu, merupakan unsur unik dalam budaya Bali.
|
Kalender atau penanggalan Bali sangat
penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Tidak seperti
kalender lain yang macamnya puluhan di dunia, kalender Bali sangat
istimewa. Penanggalan Bali adalah penanggalan "konvensi". Tidak astronomis seperti penanggalan Islam, tidak pula aritmatis seperti penanggalan Jawa, tetapi 'kira-kira' ada di antara keduanya.
|
Penanggalan Bali mirip penanggalan
luni-solar. Berdasarkan posisi matahari dan sekaligus bulan. Dikatakan
konvensi atau kompromistis, karena sepanjang perjalanan tarikhnya masih dibicarakan bagaimana cara perhitungannya. Ada beberapa cara yang dicoba diterapkan beberapa tahun (sistem Nampih Sasih)
kemudian kembali ke cara sebelumnya (Malamasa). Demikian sejalan dengan
dinamika rakyat Bali. Berikut sedikit uraian mengenai beberapa
tantangan yang ditemui dalam memformat kalender Bali secara komputasi
komputer di kelir babadbali.com.
|
Dalam kompromi sudah disepakati bahwa: 1
hari candra = 1 hari surya. Kenyataannya 1 hari candra tidak sama dengan
panjang dari 1 hari surya. Untuk itu setiap 63 hari (9 wuku) ditetapkan
satu hari-surya yang nilainya sama dengan dua hari-candra. Hari ini
dinamakan pangunalatri. Hal ini tidak sulit
diterapkan dalam teori aritmatika. Derajat ketelitiannya cukup bagus,
hanya memerlukan 1 hari koreksi dalam seratusan tahun. Karena itu dalam
kelir babadbali.com disandingkan phase bulan secara perhitungan Bali
dengan phase bulan secara astronomik.
|
Dalam 1 bulan candra atau sasih, disepakati ada 30 hari terdiri dari 15 hari menjelang purnama disebut penanggal atau suklapaksa, diikuti dengan 15 hari menjelang bulan baru (tilem) disebut panglong atau kresnakapsa. Penanggal ditulis dari 1 pada bulan baru, sampai 15 yaitu purnama, menggunakan warna merah pada kalender cetakan. Setelah purnama, kembali siklus diulang dari angka 1 pada sehari setelah purnama sampai 15 pada bulan mati (tilem) menggunakan warna hitam. Dalam perhitungan matematis, untuk membedakan warna, sering dipakai titi.
Titi adalah angka urut dari 1 yaitu bulan baru, sampai 30 pada bulan
mati. Angka 1 sampai 15 mewakili angka merah atau penanggal, 16 sampai
30 mewakili angka 1 sampai 15 angka berwarna hitam atau panglong.
Panjang bulan surya juga tidak sama dengan panjang sasih
(bulan candra). Sasih panjangnya berfluktuasi tergantung kepada jarak
bulan dengan bumi dalam orbit elipsnya. Sehingga kurun tahun surya
kira-kira 11 hari lebih panjang dari tahun candra. Untuk menyelaraskan
itu, setiap kira-kira 3 tahun candra disisipkan satu sasih tambahan.
Penambahan sasih ini masih agak rancu peletakannya. Inilah tantangan
bagi dunia aritmatika. Idealnya awal tahun surya jatuh pada paruh-akhir
sasih keenam (Kanem) atau paruh-awal sasih ketujuh (Kapitu), sehingga tahun baru Saka (hari raya Nyepi) selalu jatuh di sekitar paruh-akhir bulan Maret sampai paruh-awal bulan April.
|
Tahun baru bagi penanggalan Bali,
diperingati sebagai hari raya Nyepi, bukan jatuh pada sasih pertama
(Kasa), tetapi pada sasih kesepuluh (Kadasa). Idealnya pada penanggal 1,
yaitu 1 hari setelah bulan mati (tilem). Pada tahun 1993, Hari raya
Nyepi jatuh pada penanggal 2, diundur 1 hari, karena penanggal 1
bertepatan dengan pangunalatri dengan panglong 15 sasih Kasanga. Sekali
lagi kompromi diperlukan dalam perhitungan ini.
|
Sejak hari raya Nyepi, angka tahun Saka
bertambah 1 tahun. Menjadi angka tahun surya Masehi dikurangi 78. Dengan
demikian sasih- sasih sebelum itu berangka tahun Masehi minus 79. Hal
ini akan terasa janggal bagi pengguna penanggalan Masehi, karena angka
tahun sasih Kasanga satu tahun dibelakang angka tahun sasih Kedasa, dan
angka tahun dari sasih terakhir, Desta (Jiyestha) sama dengan angka
tahun berikutnya untuk sasih pertama (Kasa).
|
Banyak piodalan pura di Bali ditetapkan menurut kalender Saka. Beberapa hari suci juga berdasarkan tahun Saka, misalnya Hari Raya Nyepi dan Hari Suci Siwaratri.
Dewasa ayu untuk berbagai keperluan pertanian dan industri juga sangat
bergantung kepada tahun Saka, karena tahun Saka erat kaitannya dengan
perjalanan musim. Pada kalender cetakan yang dibuat oleh pakar-pakar
kalender Bali (pelopornya adalah pak Ketut Bangbang Gede Rawi)
hampir tidak ada lagi ruangan untuk mencatat kejadian lain. Sudah penuh
dengan segala petunjuk dan analisa tentang baik buruknya setiap hari.
Itupun belum cukup, di belakang lembaran2 kalender itu selalu tercetak
dengan sangat padat, informasi tentang banyak hal yang kaitannya sangat
erat dengan perjalanan sang waktu. Walaupun demikian pentingnya kalender
Bali, nampak selalu dicetak dengan kualitas seadanya, kalah dengan
kertas mengkilap dan cetakan offset seperti kalender bergambar artis.
:-))
|
Sayang sekali lagi, kalender Bali nampaknya
hanya sampai pada tahap ini. Peranan generasi muda Bali tidak ada sama
sekali. Pengkinian (update) nampaknya hanya pada angka dan kurunnya
saja. Aktifitas-aktifitas yang tercakup seperti: hari baik untuk
mencocok hidung kerbau, hari baik untuk menaikkan padi ke lumbung dan
sebagainya, walaupun sudah langka untuk budaya kini, masih tetap ajeg
tercantum seperti di lontar aslinya.
|
Beberapa tokoh kalender Bali
- I Ketut Bangbang Gede Rawi (alm) dan putra-putranya
- I Wayan Gina
- Kebek Sukarsa
- I Made Bija
Pujian babadbali.com kepada tokoh-tokoh di
atas. Masih ada yang lainnya, tetapi karena sempitnya pengetahuan kami
masih belum tertuang dalam kelir ini, mohon informasi dari para semeton
semuanya. Usaha mereka merupakan pelita dalam temaramnya budaya Bali.
Jaminan keajegan melalui kotak-kotak berangka merah dan hitam sarat dan
melimpah informasi sungguh pasti dapat merenangi waktu tanpa khawatir
tersendat, selama kalender Bali tetap diminati. Terimakasih juga kepada
perusahaan-perusahaan yang memperkenalkan produk dan usaha mereka
melalui pencetakan kalender Bali melalui berbagai percetakan, mari kita
dorong bersama ambang ketinggian budaya kita, agar tidak direndahkan
siapapun.
Perintis Kalender Bali
Ketut Bangbang Gde Rawi (1910-1989)
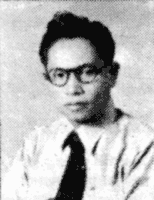 Beliau lahir di Desa Celuk, Sukawati, Sabtu Pon Sinta 17 September 1910 sebagai anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Jro Mangku Wayan Bangbang Mulat dan Jro Mangku Nyoman Rasmi.
Beliau lahir di Desa Celuk, Sukawati, Sabtu Pon Sinta 17 September 1910 sebagai anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Jro Mangku Wayan Bangbang Mulat dan Jro Mangku Nyoman Rasmi.Tahun 1929, setelah tamat sekolah Goebernemen Negeri di Sukawati, dalam usia 19 tahun, Ketut Bangbang Gde Rawi sudah mulai tekun mempelajari ihwal wariga, adat, dan filsafat agama Hindu.
Proses perburuan ilmu ini dilakukan dengan cara bertandang ke griya-griya, mencari lontar, menekuni wariga dan berdiskusi dengan peranda-peranda.
Di samping menekuni ilmu wariga, Rawi juga tertarik pada bidang seni tari dan seni rupa, seperti memahat dan melukis, dilakukan sepanjang tahun 1930-an.
Dekade ini, Ketut Bangbang Gde Rawi yang ulet bekerja juga pernah menjadi tukang jahit, jual-beli pakaian jadi, dan perhiasan emas.
Awal 1940-an, sebelum Indonesia merdeka,
beliau pernah menjadi perbekel di desa kelahirannya, Celuk. Saat itulah,
Rawi yang mewarisi banyak pustaka lontar sering dimintai untuk mencari
hari baik untuk pelaksanaan upacara atau kegiatan adat lainnya.
Lama-kelamaan, bakat beliau di bidang menentukan hari baik untuk
melakukan sesuatu (padewasaan) mulai tumbuh dan tersiar di kalangan
masyarakat luas sehingga beliau didesak oleh para tokoh adat dan agama
se-Kabupaten Gianyar untuk menyusun kalender. Desakan itu ditolak dengan
rasa rendah hati.
Namun, dalam rapat-rapat sulinggih Bali
Lombok antara tahun 1948-1949, muncullah keputusan untuk memberikan
kepercayaan kepada beliau untuk membuat kalender Bali. Tampaknya
keputusan ini sulit beliau tolak. Setahun kemudian, atas dorongan Ida Pedanda Made Kemenuh,
Ketua Paruman Pandita Bali-Lombok, Rawi mulai menyusun kalender.
Kalender hasil karya beliau yang pertama dicetak penerbit Pustaka
Balimas, salah satu penerbit besar di Bali saat itu. Tahun 1954, beliau
dilantik menjadi anggota DPRD Bali berkat keahliannya di bidang adat dan
agama.
Banyak intelektual Bali mencoba menyusun
kalender, tetapi sampai tahun 1980-an, praktis kalender Ketut Bangbang
Gde Rawi yang populer dan banyak dijadikan pegangan oleh masyarakat.
Selain karena isinya yang diyakini ketepatannya, yang khas dalam
kalendernya adalah pemasangan foto diri yang mengenakan dasi dan
kacamata. Mengapa bukan foto yang mengenakan destar? Tak jelas, tetapi
foto berdasi itu adalah potret beliau sebagai anggota DPRD Propinsi
Bali. Semula foto itu dipasang di kalender sebagai tanda pengenal
semata, tetapi lama-lama menjadi merk dagang (trade mark). Kalender
beliau tampil khas, pinggirannnya dihiasi dengan pepatran ukiran
dedaunan, di atasnya tercetak gambar swastika simbol agama Hindu.
Menurut Jro Mangku Nyoman Bambang Bayu Rahayu,
cucu Ketut Bangbang Gde Rawi yang kini menjadi penerus penyusunan
kalender, bentuk, bingkai, ilustrasi, susunan hari, potret diri dan nama
penyusun kalender itu sudah dipatenkan sejak April 2002. Ini berarti
model kalender beliau tidak boleh dijiplak. Meski demikian, kalender
Bali lain yang muncul belakangan mau tak mau mengikuti pola kalender
Ketut Bangbang Gde Rawi meski tidak persis sama.
Kecemerlangan Rawi di bidang adat, wariga,
dan agama Hindu mendapat pengakuan dari Institut Hindu Dharma (IHD, kini
Unhi). Buktinya, tahun 1972, beliau ditunjuk menjadi dosen untuk mata
kuliah "wariga" di IHD. Tahun 1976, beliau juga mengabdikan diri di
Parisadha Hindhu Dharma Pusat yang berkedudukan di Denpasar sebagai
anggota komisi penelitian. Selain membuat kalender dan mengajar, Rawi
juga menerbitkan beberapa buku, seperti Kunci Wariga (dua jilid, 1967)
dan Buku Suci Prama Tatwa Suksma Agama Hindu Bali (1962).
Ketut Bambang Gde Rawi meninggal 18 April 1989
dengan mewariskan kecerdasan yang monumental, yakni pengetahuan tentang
cara menyusun kalender Bali. Sejak kepergiannya, penyusunan kalender
diteruskan oleh putranya, Made Bambang Suartha. Tugas ini dikerjakan sekitar delapan tahun, tepatnya hingga Made Bambang Suartha meninggal 10 April 1997.
Warisan ilmu menyusun kalender itu kemudian menurun pada Jro Mangku Nyoman Bambang Bayu Rahayu, cucu Ketut Bangbang Gde Rawi. Sampai sekarang kalender Ketut Bangbang Gde Rawi tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Di bawah potret Ketut Bangbang Gde Rawi tertera tulisan "Disusun oleh Ketut Bangbang Gde Rawi (alm) dan Putra-putranya".
Warisan ilmu menyusun kalender itu kemudian menurun pada Jro Mangku Nyoman Bambang Bayu Rahayu, cucu Ketut Bangbang Gde Rawi. Sampai sekarang kalender Ketut Bangbang Gde Rawi tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Di bawah potret Ketut Bangbang Gde Rawi tertera tulisan "Disusun oleh Ketut Bangbang Gde Rawi (alm) dan Putra-putranya".
Bagi masyarakat Bali di Bali, dan mereka
yang ada di daerah transmigran, termasuk yang menetap di luar negeri,
kalender Bali sudah menjadi kebutuhan. Dengan menggantung kalender Bali
di rumah, mereka dengan mudah bisa mengetahui hari khusus agama Hindu
seperti purnama tilem, Galungan Kuningan, Nyepi dan sebagainya.
Belakangan sejumlah ahli penyusun kalender
Bali yang lain selain "dinasti Ketut Bangbang Gde Rawi", juga
bermunculan dan mereka berhasil membuat kalender yang diterima publik.
Perkembangan penyusunan kalender Bali ini tentu tak bisa dipisahkan dari
jasa Bambang Gde Rawi, sang perintis. Usaha Rawi dan penyusun kalender
Bali lainnya besar jasanya kepada masyarakat dalam usaha menjaga
kearifan lokal Bali.
RUTE PERJALANAN
RUTE PERJALANAN
WUKU KELAHIRAN FAMILY
TGL : 01 Agustus 1971 |
TGL : 20 Pebruari 1972 |
TGL : 24 Maret 1998 |
TGL : 03 September 2000 |
TGL : 05 Juli 2005 |